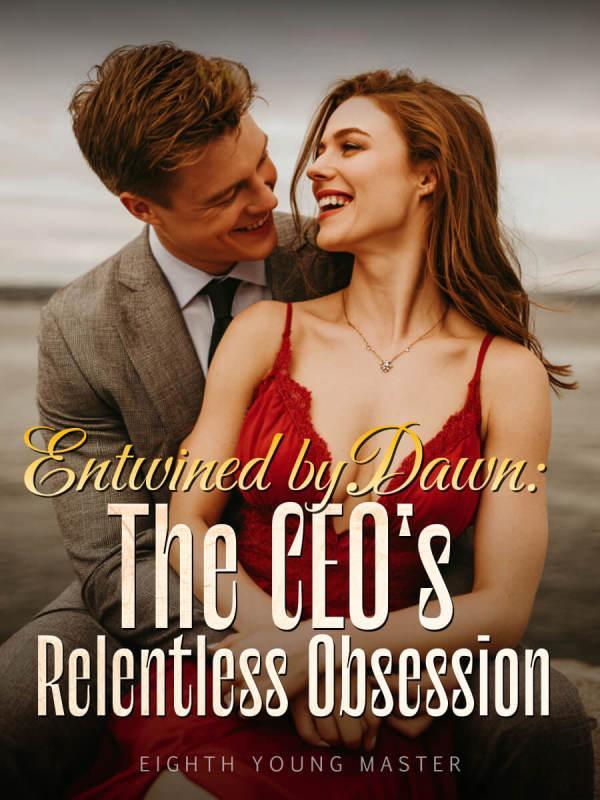©Novel Buddy
The Shattered Light-Chapter 115: – Pintu yang Tak Pernah Tertutup
Langkah-langkah mereka senyap saat melintasi bayangan malam yang menyelimuti dataran perak Menara Cahaya Baru. Tak ada alarm. Tak ada penjaga yang menghalangi. Hanya sunyi—terlalu sunyi.
Kaelen memimpin, mengenakan kembali jubah gelapnya. Tapi kali ini, dia tidak bersembunyi. Wajahnya tegak. Tatapannya tajam.
Serina berjalan tepat di belakangnya, anak panah sudah terjepit di busurnya. Alden di sisi kanan, tangannya menggenggam belati yang dibalut api biru lembut.
“Menara ini terasa...” Alden berbisik, “... seperti sedang menunggu kita.”
Kaelen tidak menjawab. Tapi dalam dadanya, ada getaran. Sesuatu... yang mengenal dirinya. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai tamu. Tapi sebagai bagian dari dirinya sendiri.
Begitu mereka melangkah melewati koridor kristal pertama, dindingnya menyala dengan ukiran—bukan simbol Cahaya Baru seperti yang terlihat di luar—tapi bayangan siluet masa lalu: dua anak kecil, duduk di bawah pohon terang. Salah satu memegang buku. Satunya pedang kayu.
Kaelen berhenti.
Serina menatapnya. “Kau kenal tempat ini?”
Ia mengangguk. “Ini bukan Menara Cahaya Baru. Ini... dulu rumah kami.”
Alden mengernyit. “Rumah siapa?”
Kaelen menatap salah satu ukiran. Sosok anak kecil itu tersenyum kepadanya.
“Lucien dan aku.”
Tiba-tiba, lorong bergetar. Cahaya memucat. Dunia di sekeliling mereka larut dalam kabut tipis.
Kaelen menoleh, tapi Serina dan Alden tidak lagi terlihat.
Ia berdiri di kamar kecil. Jendela terbuka, angin bertiup lembut. Di luar, padang hijau dan langit biru—pemandangan masa kecil yang telah hilang.
Seseorang duduk di lantai. Seorang anak lelaki. Rambutnya putih keperakan. Mata kelabu terang. Lucien.
“Kaelen!” anak itu berseru riang. “Lihat, aku bisa buat cahaya dari tanganku!”
Kaelen mundur selangkah.
“Ini bukan nyata. Ini jebakan.”
Tapi sesuatu dalam dirinya tak bisa berhenti menatap anak itu. Kebahagiaan dalam matanya—bukan manipulasi, bukan ambisi. Hanya... saudara kecil yang bangga menunjukkan keajaiban kecilnya.
“Kenapa kau tinggalkan aku, Kaelen?” suara Lucien kecil berubah lirih. “Kenapa kau pilih mereka, bukan aku?”
Kaelen menutup mata.
“Aku tidak ingat,” jawabnya. “Dan mungkin itu yang paling menyakitkan.”
Ketika ia membuka mata, ilusi memudar—dan digantikan oleh kenyataan brutal. Ia terlempar ke dalam aula pusat menara, dan Lucien dewasa berdiri di ujungnya, tubuhnya dibungkus cahaya yang memancar dari Relik terakhir yang mengambang di tengah ruangan.
“Selamat datang kembali, saudaraku,” ucap Lucien.
Serina dan Alden muncul dari sisi kanan dan kiri, terjatuh dari celah ilusi. Luka di tangan mereka menunjukkan bahwa mereka juga dipaksa menghadapi masa lalu masing-masing.
“Relik itu...” Serina menyipitkan mata. “...mengikat ingatan kita?”
Lucien tersenyum. “Ia memanggil siapa pun yang berdarah penjaga. Tapi hanya satu yang akan diterima.”
Kaelen melangkah maju.
“Aku tidak datang untuk menguasainya,” katanya. “Aku datang untuk menghentikanmu.”
Lucien mengangkat tangan. Cahaya menyelimuti tubuhnya seperti pelindung. “Lalu kita buktikan siapa yang lebih layak.”
Pertarungan pecah dengan kecepatan menakutkan. Kaelen mengayunkan pedangnya, gelombang bayangan meledak ke depan. Lucien menangkisnya dengan sinar murni, lalu menyerang balik dengan peluru cahaya yang meledak di tanah seperti bintang jatuh.
Serina menembakkan panah ke sisi Lucien, tapi cahayanya menekuk arah anak panah. Alden mencoba mendekat dari belakang, namun terpental oleh medan tak kasatmata.
“Ini bukan tentang siapa yang kuat,” kata Lucien, suaranya bergema. “Ini tentang siapa yang diizinkan oleh Relik.”
Kaelen menggertakkan gigi. Tubuhnya mulai retak oleh energi gelap yang mengalir terlalu deras. Tapi ia tetap melangkah. Langkah demi langkah, menembus medan cahaya.
Lucien melepaskan ledakan terakhir—dan Kaelen menerimanya langsung.
Tubuhnya terhantam mundur, tergeletak. Tapi saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu...
Relik itu... bersinar dengan dua warna.
Hitam dan putih.
Kaelen bangkit. Perlahan. Luka membakar tubuhnya, tapi ia berdiri.
“Relik ini tidak milikmu,” katanya. “Dan juga bukan milikku.”
Lucien menegang.
“Relik ini adalah kenangan. Luka. Harapan. Dan hanya mereka yang mampu menanggung semuanya... yang bisa menjaganya.”
Relik menyala terang—dan sebuah bentuk baru muncul di udara. Bukan pedang. Bukan tongkat.
Tapi cermin.
Lucien menatap pantulannya sendiri—dan ia melihat wajah kecilnya, sendirian.
Kaelen menunduk, air mata mengalir.
“Aku menyesal. Bukan karena meninggalkanmu. Tapi karena aku tak cukup kuat untuk mengingat.”
Tiba-tiba, suara lain menggema dari dinding.
“Sayangnya, kalian berdua terlalu lambat.”
Bayangan ketiga muncul. Sosok berjubah, wajahnya tersembunyi. Dari balik jubahnya, tangan hitam meluncur dan menembus tubuh Relik.
Cahaya dan bayangan meledak bersamaan.
Dan dunia kembali berubah.